Sekitar 1.000 tahun yang lalu, sekelompok kecil orang Polinesia berlayar ribuan mil melintasi Pasifik untuk menetap di salah satu tempat paling terpencil di dunia—sebuah pulau kecil yang sebelumnya tidak berpenghuni yang mereka beri nama Rapa Nui. Di sana, mereka mendirikan ratusan “moai”, atau patung batu raksasa yang kini terkenal sebagai simbol peradaban yang punah. Pada akhirnya, jumlah mereka membengkak hingga mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan; mereka menebang semua pohon, membunuh burung laut, menguras tanah dan akhirnya merusak lingkungan mereka. Populasi dan peradaban mereka runtuh, hanya tersisa beberapa ribu orang ketika orang Eropa menemukan pulau itu pada tahun 1722 dan menyebutnya Pulau Paskah. Setidaknya itulah cerita lama, yang diceritakan dalam studi akademis dan buku-buku populer seperti “Collapse” karya Jared Diamond tahun 2005.
Sebuah studi baru menantang narasi ekosida ini, dengan mengatakan bahwa populasi Rapa Nui tidak pernah meningkat ke tingkat yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, para pemukim menemukan cara untuk mengatasi keterbatasan yang keras di pulau itu, dan menjaga populasi tetap kecil dan stabil selama berabad-abad. Buktinya: inventaris baru yang canggih dari “taman batu” yang cerdik tempat penduduk pulau menanam ubi jalar bergizi tinggi, makanan pokok mereka. Taman-taman tersebut hanya mencakup area yang cukup untuk menampung beberapa ribu orang, kata para peneliti. Studi ini baru saja dipublikasikan di jurnal Science Advances.
“Ini menunjukkan bahwa populasinya tidak sebesar perkiraan sebelumnya,” kata penulis utama Dylan Davis, seorang peneliti pascadoktoral di bidang arkeologi di Columbia Climate School. “Ajarannya berlawanan dengan teori keruntuhan. Masyarakat bisa menjadi sangat tangguh dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dengan memodifikasi lingkungan dengan cara yang bermanfaat.”

Pulau Paskah bisa dibilang merupakan tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, dan salah satu yang terakhir untuk diselesaikan oleh manusia, jika bukan yang terakhir. Daratan kontinental terdekat adalah Chili tengah, hampir 2.200 mil ke arah timur. Sekitar 3.200 mil ke arah barat terletak Kepulauan Cook yang tropis, tempat para pemukim diperkirakan telah berlayar sejak sekitar tahun 1200 Masehi.
Pulau seluas 63 mil persegi ini seluruhnya terbuat dari batuan vulkanik, namun tidak seperti pulau tropis subur seperti Hawaii dan Tahiti, letusannya berhenti ratusan ribu tahun yang lalu, dan nutrisi mineral yang dibawa oleh lahar telah lama terkikis dari tanah. Terletak di wilayah subtropis, pulau ini juga lebih kering dibandingkan pulau tropis lainnya. Tantangannya lebih besar lagi, air laut di sekitarnya turun drastis, yang berarti penduduk pulau harus bekerja lebih keras untuk memanen makhluk laut dibandingkan mereka yang tinggal di pulau-pulau Polinesia yang memiliki laguna dan terumbu karang yang mudah diakses dan produktif.
Untuk mengatasinya, pemukim menggunakan teknik yang disebut rock gardening, atau litik mulsa. Ini terdiri dari hamburan bebatuan di permukaan rendah yang setidaknya sebagian terlindung dari semprotan garam dan angin. Di celah-celah batu, mereka menanam ubi jalar. Penelitian telah menunjukkan bahwa bebatuan mulai dari ukuran bola golf hingga batu besar mengganggu pengeringan angin dan menciptakan turbulensi aliran udara, menurunkan suhu permukaan tertinggi di siang hari dan meningkatkan suhu terendah di malam hari. Fragmen yang lebih kecil, yang dipecah dengan tangan, memperlihatkan permukaan segar yang sarat dengan nutrisi mineral yang dilepaskan ke dalam tanah seiring dengan cuaca. Beberapa penduduk pulau masih memanfaatkan kebun, namun meski dengan tenaga kerja yang banyak, produktivitas mereka masih rendah. Teknik ini juga telah digunakan oleh masyarakat adat di Selandia Baru, Kepulauan Canary, dan Amerika Barat Daya, serta tempat-tempat lain.
Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa populasi pulau itu dulunya lebih besar dari 3.000 atau lebih penduduk yang pertama kali diamati oleh orang Eropa, sebagian karena besarnya moai; dibutuhkan banyak orang untuk membangunnya, demikian alasannya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti telah berupaya memperkirakan populasi ini dengan menyelidiki tingkat taman batu dan kapasitas produksi. Orang-orang Eropa awal memperkirakan bahwa mereka menguasai 10% wilayah pulau itu. studi tahun 2013 berdasarkan citra satelit visual dan inframerah dekat menghasilkan 2,5% hingga 12,5% Satu lagi belajar pada tahun 2017 mengidentifikasi sekitar 7.700 hektar, atau 19% dari luas pulau, cocok untuk ubi jalar. Dengan membuat berbagai asumsi tentang hasil panen dan faktor lainnya, penelitian memperkirakan populasi di masa lalu mungkin mencapai 17.500, atau bahkan 25.000, meskipun mungkin juga jauh lebih rendah.

Dalam studi baru ini, anggota tim peneliti melakukan survei lapangan terhadap taman batu dan karakteristiknya selama lima tahun. Dengan menggunakan data ini, mereka kemudian melatih serangkaian model pembelajaran mesin untuk mendeteksi taman tersebut melalui citra satelit yang disesuaikan dengan spektrum inframerah gelombang pendek yang baru tersedia, yang tidak hanya menyoroti batuan, tetapi juga tempat-tempat dengan kelembapan tanah dan nitrogen yang lebih tinggi, yang merupakan fitur utama Taman .
Para peneliti menyimpulkan bahwa taman batu tersebut hanya menempati lahan seluas sekitar 188 hektar—kurang dari setengah persen luas pulau. Mereka mengatakan bahwa mereka mungkin melewatkan beberapa hal kecil, namun tidak cukup untuk membuat perbedaan besar. Dengan membuat serangkaian asumsi, mereka mengatakan bahwa jika seluruh pola makan didasarkan pada ubi jalar, kebun tersebut mungkin dapat menghidupi sekitar 2.000 orang. Namun, berdasarkan isotop yang ditemukan pada tulang dan gigi serta bukti lainnya, orang-orang di masa lalu mungkin memperoleh 35% hingga 45% makanan mereka dari sumber laut, dan sejumlah kecil dari tanaman lain yang kurang bergizi seperti pisang, talas, dan tebu. . Dengan memperhitungkan sumber daya ini akan meningkatkan daya dukung populasi menjadi sekitar 3.000—jumlah yang diamati selama kontak dengan Eropa.
“Ada singkapan batu alam di mana-mana yang di masa lalu salah diidentifikasi sebagai taman batu. Citra gelombang pendek memberikan gambaran berbeda,” kata Davis.
Carl Lipo, seorang arkeolog di Universitas Binghamton dan salah satu penulis studi tersebut, mengatakan bahwa gagasan tentang ledakan dan kehancuran populasi “masih meresap ke dalam pikiran masyarakat” dan di berbagai bidang termasuk ekologi, namun para arkeolog diam-diam mundur darinya. Mengumpulkan bukti berdasarkan penanggalan radiokarbon pada artefak dan sisa-sisa manusia tidak mendukung gagasan adanya populasi besar, katanya. “Gaya hidup masyarakat pasti sangat sulit,” ujarnya. “Pikirkan tentang duduk-duduk memecahkan batu sepanjang hari.”
Populasi pulau ini sekarang mendekati 8.000 (ditambah sekitar 100.000 wisatawan per tahun). Sebagian besar makanan kini diimpor, namun beberapa penduduk masih menanam ubi jalar di kebun kuno – sebuah praktik yang berkembang selama penutupan pandemi Covid pada tahun 2020-2021, ketika impor dibatasi. Beberapa juga beralih ke teknik bercocok tanam di lahan luas, membajak lahan, dan menggunakan pupuk buatan. Namun hal ini sepertinya tidak akan berkelanjutan, kata Lipo, karena hal ini akan semakin mengurangi tipisnya tutupan lahan.
Seth Quintus, antropolog di Universitas Hawaii yang tidak terlibat dalam penelitian ini, mengatakan ia melihat pulau tersebut sebagai “studi kasus yang baik dalam adaptasi perilaku manusia dalam menghadapi lingkungan yang dinamis.” Studi baru dan studi serupa lainnya “memberikan peluang untuk mendokumentasikan dengan lebih baik sifat dan tingkat strategi adaptasi,” katanya. “Bertahan hidup di wilayah subtropis Rapa Nui yang lebih gersang dan lebih terpencil dan secara geologis merupakan tantangan besar.”
Studi ini juga ditulis bersama oleh Robert DiNapoli dari Binghamton University; Gina Pakarati, peneliti independen di Rapa Nui; dan Terry Hunt dari Universitas Arizona.






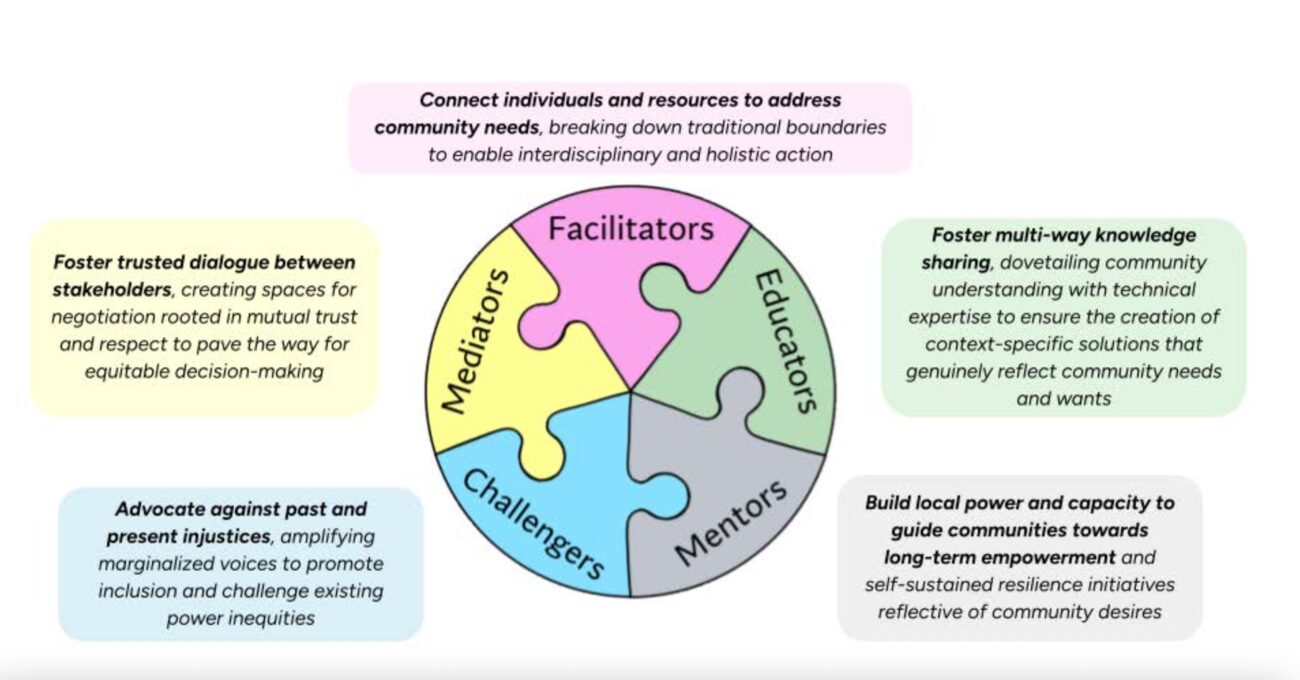

Tinggalkan Balasan