
Perjalanan saya dari New York City ke Baku, Azerbaijan, tuan rumah tahun ini Konferensi perubahan iklim PBB (COP29), membawa saya lebih dari tujuh ribu mil dari darat dan laut. Saya tiba di Baku pada malam hari, di mana menara berwarna-warni berbentuk api menghiasi pemandangan kota. Dulunya merupakan republik Soviet dan sekarang menjadi negara minyak yang kaya minyak, Azerbaijan berbatasan dengan Iran, Armenia, dan Rusia.
Selama dua minggu berikutnya, lebih dari 60.000 pemimpin dunia, pakar dan anggota masyarakat sipil bertukar gagasan dan informasi, sementara negosiasi tingkat tinggi dengan perwakilan dari hampir 200 negara berlangsung di ruang yang aman.
Saya bertugas di komite pengarah Hiburan & Budaya UNFCCC untuk Film & TV Aksi Iklim (ECCA). Sebagai seorang pendidik, pembuat film, dan pemimpin iklim di industri hiburan, saya tertarik untuk mengikuti perbincangan seputar keuangan, migrasi manusia, dan peran budaya sebagai solusi iklim. Saya menyoroti isu ini dalam kursus Climate School saya, Climate Change: The Art of Storytelling, the Zeitgeist and Our Future. Mewakili 11 negara dan 10 negara bagian AS, kami adalah ruang kelas interdisipliner yang terdiri dari siswa-siswa penuh semangat dari Sekolah Iklim, Sekolah Seni, arsitektur, dan kebijakan internasional. Kami mengkaji tema-tema iklim geopolitik yang kompleks dan mengeksplorasi pendekatan-pendekatan unik dalam solusi iklim. Kami menciptakan cerita yang sangat diperlukan dalam industri hiburan dan budaya global, termasuk film, televisi, penulisan kreatif, teater, dan media digital.

Ketika kita berpikir tentang iklim, kita tidak bisa meremehkan kekuatan cerita dalam mengembangkan norma-norma perilaku, nilai-nilai dan sistem kepercayaan. Narasi berkembang dari pola cerita, karakter dan ide menarik yang muncul saat penonton terlibat dan berbagi ide. Penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan emosional dengan cerita dan pengetahuan tentang iklim dapat membangkitkan indera kita dan memicu imajinasi. Cerita, lebih dari sekedar media berita informatif, dapat memotivasi penelitian ilmiah dan keterlibatan masyarakat.
Murid-murid saya sangat khawatir dengan dampak perubahan iklim yang terjadi di negara asal mereka—kenaikan permukaan laut di Meksiko dan Malaysia, banjir besar di Pakistan, krisis panas dan air yang parah. Meskipun beberapa siswa berasal dari negara-negara yang dianggap sebagai penghasil emisi karbon tertinggi (AS, Tiongkok), siswa lainnya berasal dari negara-negara yang memiliki tingkat ketat yang tinggi—dan dalam beberapa kasus, kedua hal tersebut benar adanya. Saat semester musim gugur dimulai, seorang siswa kehilangan rumah, harta benda, dan kenangan masa kecilnya, dalam peristiwa cuaca ekstrem di Houston, Texas. Siswa lain dari Meksiko memfilmkan evakuasi paksa pantai yang pertama di negaranya.
Perjanjian Paris tahun 2015 mencakup tujuan menyeluruh untuk memberdayakan anggota masyarakat agar terlibat dalam aksi iklim melalui pendidikan, pelatihan, dan akses publik terhadap informasi. Kelas kami mengkaji peran dongeng dalam mengubah perilaku dan opini publik tentang ekstraksi, konsumsi, dan bagaimana pemanasan global mengubah hidup kita. Film independen dan budaya populer sering kali menangkap momen-momen zeitgeist yang berpotensi menginspirasi perasaan terhubung, pengertian, dan keagenan manusia. Lebih dari sekali selama COP29, saya mendengar para pembicara menyebut iklim sebagai “segalanya, di mana saja, sekaligus,” judul film pemenang Oscar tahun 2023 tentang kemanusiaan, multiverse, dan sistem “fosil” yang kita tinggali.
Climate School adalah mitra di Baku untuk menyelenggarakan “Hari Pengetahuan” di Paviliun Mobilitas Iklim, di mana pengungsian paksa dan risiko yang dirasakan menjadi topik diskusi besar. Lisa Dale, sutradara MA dalam Iklim dan Masyarakat program ini, menjadi moderator dalam sebuah panel tentang bagaimana mendorong pemukiman kembali yang bermartabat bagi mereka yang melakukan suatu bentuk mobilitas iklim. seperti yang kami dengar dari para ahli, pembuat kebijakan, dan suara-suara yang mewakili negara-negara di kawasan Selatan dan Kepulauan Pasifik. Kelas kami juga membaca buku Dale, “Adaptasi Perubahan Iklim,dimana ia bertanya, “Bagaimana seorang petani pedesaan di Bangladesh, atau walikota kecil di Iowa, atau seorang perencana kota di Tokyo, menerjemahkan kemungkinan kenaikan permukaan laut menjadi sesuatu yang berarti bagi komunitas mereka? Bagaimana para pemimpin masyarakat dan pengambil keputusan di semua tingkatan mengakses informasi ilmiah yang dapat ditindaklanjuti?”
Dalam sesi awal kami di Columbia, murid-murid saya membaca buku Amitav Ghosh tahun 2016, “The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable.” Ghosh berbicara tentang perubahan politik perubahan iklim di Anglosfer: “Daripada dilihat sebagai sebuah fenomena yang memerlukan respon praktis, seperti di Belanda dan Denmark, atau sebagai sebuah bahaya yang melekat, seperti di Maladewa dan Bangladesh, hal ini justru berdampak pada perubahan iklim. telah menjadi salah satu dari banyak permasalahan yang terjadi di sepanjang garis patahan polarisasi politik yang ekstrem.”
Salah satu topik diskusi di kelas kami adalah “iklim keheningan” di industri film besar, termasuk Hollywood. Inisiatif terbaru untuk mempromosikan “sebutan iklim” dalam program film dan televisi adalah upaya yang ringan dibandingkan dengan kampanye narasi anti-perubahan iklim selama puluhan tahun yang dilakukan oleh industri bahan bakar fosil. Hijauhushing oleh studio, dan keengganan untuk menghubungkan peristiwa cuaca ekstrem dengan pemanasan global dalam konten, kemungkinan besar karena kekhawatiran terhadap peraturan pemerintah, dan hilangnya keuntungan melalui pendapatan iklan dan penjualan tiket—terlibat dalam serangan ideologis yang didorong oleh media terhadap ilmu pengetahuan iklim.

Pada COP29, sebagai perwakilan ECCA, saya berbicara di panel tentang perlunya penyampaian cerita mengenai perubahan iklim, dan “kerja sama radikal” – sebuah istilah yang digunakan oleh PBB untuk keterlibatan multi-pemangku kepentingan, dan sebuah istilah yang menggambarkan sinergi dari proses pemikiran kelompok yang terjadi. di ruang kelas kami di New York. Saya berada dalam pusaran budaya dan cerita, bersamaan dengan negosiasi dunia nyata. Sementara itu, di New York, murid-murid saya menyuarakan keprihatinan mengenai 1.700 pelobi bahan bakar fosil yang dilaporkan menghadiri konferensi tersebut. Mereka membahas “Borgen: Power & Glory,” serial Denmark di Netflix, di mana Greenland menemukan minyak dan menteri luar negeri terpaksa menghadapi hubungannya sendiri dengan ambisi, nilai-nilai politik, dan posisi kekuasaannya.
Di Baku, para pemimpin di Pasifik, Karibia, dan Afrika berdebat sengit, mendesak negara-negara yang lebih kaya dan ekstraktif mengambil tindakan. Hambatan yang dihadapi industri minyak telah terlihat jelas. Para delegasi berjuang dalam perundingan yang tegang dan penuh konflik untuk mencapai konsensus mengenai tujuan pendanaan iklim global yang baru. Seiring berjalannya waktu, target tersebut ditingkatkan menjadi $300 miliar per tahun pada tahun 2035—jauh dari kebutuhan negara-negara rentan yang kelangsungan hidupnya dipertaruhkan akibat kenaikan permukaan air laut, kelangkaan sumber daya, dan panas ekstrem.
Selama berada di COP29, saya berinteraksi dengan berbagai pakar, jurnalis, dan tokoh masyarakat seperti Bridget Kakuwa, seorang petani di Botswana yang bekerja dengan Departemen Pertanian sebagai penghubung antara petani dan pemerintah. Saya bertemu Teddy Mugabo, CEO perempuan pertama dari Rwanda Green Fund, yang bekerja di negara dengan 70% penduduknya berusia di bawah 30 tahun, dan pembangkit listrik tenaga air dan surya menyumbang 53% dari total listrik yang dihasilkan.
Di Climate School, murid-murid saya sudah mulai fokus pada tugas akhir mereka. Dengan menggunakan elemen ilmu pengetahuan iklim dan budaya populer, mereka berupaya melibatkan pemirsa dalam percakapan yang menginspirasi tentang masa depan kita. Dengan menjalin hubungan dari kerja kolektif kami dengan seni bercerita visual dan sastra, mereka menciptakan proposal yang mengesankan untuk animasi yang mengubah perspektif, fitur dramatis, film pendek, dan proposal buku untuk cerita multikultural.
Saat menyampaikan percakapan yang sering bergejolak dari COP29 kepada siswa saya, saya melihat lebih dari sebelumnya bahwa pendekatan multidisiplin terhadap iklim tidak hanya radikal, namun juga penting. Dengan berinvestasi pada imajinasi dan narasi kita, kita dapat mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan solusi ilmiah; kami dapat membantu semua negara yang sangat membutuhkan sumber daya dan dana untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan iklim.
Kita harus bekerja secara kolektif sebagai seniman, warga negara, petani, ilmuwan, humanis, insinyur, pakar, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan cerita demi masa depan yang lebih sehat dan aman bagi keluarga, komunitas, dan negara kita—dan untuk generasi mendatang.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah milik penulis, dan tidak mencerminkan posisi resmi Columbia Climate School, Earth Institute, atau Columbia University.






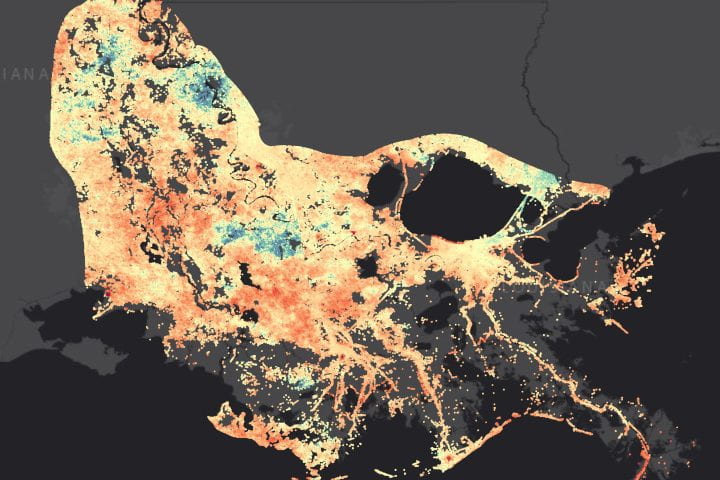

Tinggalkan Balasan