COP30 telah berakhir, negosiasi telah ditutup dan para pemimpin global telah pulang. Namun bagi jutaan orang yang berada di garis depan krisis iklim, hal ini belum berakhir. Banjir tidak kunjung surut. Tanaman yang rusak tidak dapat dikembalikan. Badai berikutnya tidak berhenti menunggu pertemuan puncak berikutnya.
Di Sudan Selatan, tempat saya tumbuh dewasakrisis iklim tidak pernah menjadi ancaman jangka panjang. Ini adalah tekstur kehidupan sehari-hari. Desa leluhurku Jalle, Bor– Tempat kakek saya dimakamkan – telah berada di bawah air selama bertahun-tahun. Sekitar 700.000 Masyarakat Sudan Selatan mengalami bencana banjir setiap tahunnya, sama seperti masyarakat rentan lainnya di seluruh dunia. Ketika air banjir meningkat, rumah-rumah hilang, penyakit menyebar dan banyak keluarga semakin terjerumus ke dalam kemiskinan. Hasilnya, saat ini, lebih dari 76 persen Masyarakat Sudan Selatan hidup di bawah garis kemiskinan.

Ketika kita masih anak-anak, kita mengandalkan pengetahuan orang tua kita – kicauan burung, bentuk awan, ritme angin – untuk membaca cuaca. Namun perubahan yang disebabkan oleh manusia membuat alam tidak dapat dikenali lagi. Tanda-tandanya tidak lagi sesuai dengan apa yang diketahui orang tua dan kakek nenek kita. Iklim yang kita warisi telah digantikan oleh sesuatu yang asing dan tidak dapat diterima.
Kemudian, saat hidup sebagai pengungsi di Uganda, saya belajar pertanian untuk mengatasi kelaparan yang membentuk kehidupan kami. Tapi satu musim, Banjir menyapu bersih 90 persen tanaman saya. Saya menyadari bahwa ketahanan iklim membutuhkan lebih dari sekedar benih dan harapan. Itu membutuhkan pemahaman.
Kesadaran itu membawa saya ke sana Sekolah Iklim Columbia dan akhirnya magang bersama Tim Aksi Iklim Sekretaris Jenderal PBBtempat saya menganalisis rencana iklim nasional dari hampir 200 negara. Saya mengikuti COP30 dengan cermat, mengamati perkembangan diplomasi. Perdebatan ini membahas tentang fase fosil yang intens, pendanaan dan tanggung jawab adaptasi. Namun sebagai seseorang yang kenangan masa kecilnya dibangun di atas bencana dan adaptasi terus-menerus, kesenjangan antara ruang konsultasi dan dunia nyata semakin lebar.
Kolombia Global baru-baru ini membagikan perjalanan sayamengutip Asisten Sekretaris Jenderal Selwin Hart, yang mengatakan: “Pada saat ketidakpastian dan perpecahan geopolitik… Anyeth membantu memastikan bahwa suara mereka yang berada di garis depan krisis iklim didengar, dihormati dan tidak dilupakan.”
Namun, COP30 sekali lagi menunjukkan seberapa jauh kebijakan iklim global masih berbeda dengan pengalaman masyarakat garis depan.
Konferensi ini membahas mengenai bahan bakar fosil, tanpa adanya kesepakatan besar mengenai pendanaan iklim, sementara dunia terus berinvestasi dalam adaptasi – sebuah bidang yang akan menentukan apakah manusia dapat bertahan hidup dari pemanasan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Investasi tiga kali lipat dalam penyesuaiansebagai konferensi yang sudah diselesaikan, tidak menjadi masalah; Masalahnya adalah bagaimana dan oleh negara mana hal ini akan dibiayai dan bagaimana investasi tersebut akan sampai kepada masyarakat yang dituju. Adaptasi bukanlah pembicaraan sampingan; Itu adalah garis hidup.
Bagi masyarakat seperti saya, adaptasi berarti sistem peringatan dini yang benar-benar menjangkau desa-desa. Ini berarti pertahanan terhadap banjir tetap bertahan. Hal ini berarti pertanian iklim, air minum yang aman, infrastruktur yang andal, dan sistem kesehatan yang siap menghadapi wabah penyakit. Artinya, kekuasaan pengambilan keputusan ada di tangan orang-orang yang mengalami krisis, bukan hanya mereka yang memperdebatkannya.
Adaptasi juga merupakan masalah kesetaraan. Orang-orang yang paling menderita akibat dampak iklim adalah pihak yang paling sedikit menyebabkan dampak perubahan iklim. Namun, janji pendanaan adaptasi masih belum terealisasi. Komitmen yang dilanggar telah menjadi bentuk ketidakadilan iklim.
Sebagai seseorang yang kenangan masa kecilnya dibangun di atas bencana dan adaptasi terus-menerus, kesenjangan antara ruang konsultasi dan dunia nyata tidak pernah terasa lebih lebar.
Ketidakseimbangan antara mitigasi dan adaptasi sangatlah berbahaya. Mitigasi memang penting, namun tidak cukup – tidak bagi petani yang lahan pertaniannya terkena banjir tahun ini dan akan mengalami hal yang sama di tahun-tahun mendatang, tidak bagi keluarga yang mengungsi akibat badai, tidak bagi desa yang tidak dapat membangun kembali dengan cepat.
Alvin Toffler pernah menulis bahwa orang yang buta huruf di abad ke-21 adalah mereka yang tidak bisa “belajar, tidak tahu, dan belajar lagi”. Visi tersebut mendefinisikan adaptasi iklim. Dunia harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri. Masyarakat harus mempelajari literasi iklim agar informasi yang salah tidak memperparah kerentanan. Pemerintah harus menghentikan kebiasaan menganggap adaptasi sebagai sebuah pilihan dan belajar untuk memprioritaskannya.
Selama COP30, Masyarakat adat melakukan protes di Belemmengklaim tempat duduk di meja. Kehadiran mereka tidak bersifat simbolis; Hal ini merupakan pengingat bahwa solusi iklim tanpa suara di garis depan tidaklah lengkap. Sistem pengetahuan masyarakat adat telah menjaga ekosistem selama berabad-abad. Hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena bumi sedang memasuki fase paling bergejolak.
Belem, yang berada di tepi dan pintu gerbang Amazon, memiliki beban emosional. Namun simbolisme bukanlah perlindungan. Simbolisme tidak menyelamatkan rumah dari keruntuhan, kegagalan panen, atau hilangnya nyawa. Yang penting saat ini adalah apakah para pemimpin dunia memperlakukan COP30 sebagai titik akhir negosiasi, atau titik awal tindakan.
KTT iklim di masa depan harus mengukur keberhasilan tidak hanya dalam keberhasilan diplomasi, namun juga dalam hal perlindungan kehidupan dan pelepasan dampak nyata di setiap sudut dunia. Mereka harus mengajukan pertanyaan seperti: Berapa banyak GRK yang telah kita hilangkan? Seberapa besar tindakan yang kita perlukan untuk mencapai net zero dan mempertahankan acuan 1,5 derajat Celsius? Siapa yang mendapat sistem peringatan dini? Siapa yang dibangun kembali? Siapa yang selamat?
Sebagai seseorang yang tumbuh besar dalam lingkungan yang kehilangan iklim dan kini bekerja dalam sistem iklim global, saya tahu betapa rapuhnya jembatan antara janji dan perlindungan. Namun saya juga mengetahui apa yang mungkin terjadi jika ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman hidup bersatu.
COP30 telah berakhir, namun krisis iklim terus berlanjut dengan kejelasan yang tak terlupakan. Bagi jutaan orang seperti saya, waktu tidak diperhitungkan dalam konferensi. Hal ini diperhitungkan dalam musim banjir dan musim kemarau, frekuensi bencana, dan menyusutnya batas antara kelangsungan hidup dan bencana.
Bagi kami, sama seperti Presiden Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva dikatakan“Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan. Ini adalah tragedi saat ini.” Dan dunia tidak lagi mampu merespons setelah kerusakan terjadi.
Anyeeth Philip Ayuen adalah lulusan MA baru-baru ini dalam bidang Iklim dan Masyarakat di Columbia Climate School. Saat ini ia bekerja sebagai Manajemen Program di Tim Aksi Iklim Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendukung analisis kontribusi yang ditentukan secara nasional, pemantauan media iklim, dan pengembangan kebijakan untuk COP30.
Pandangan dan opini yang dikemukakan di sini adalah milik penulis, dan tidak mencerminkan posisi resmi Columbia Climate School, Earth Institute, atau Columbia University.




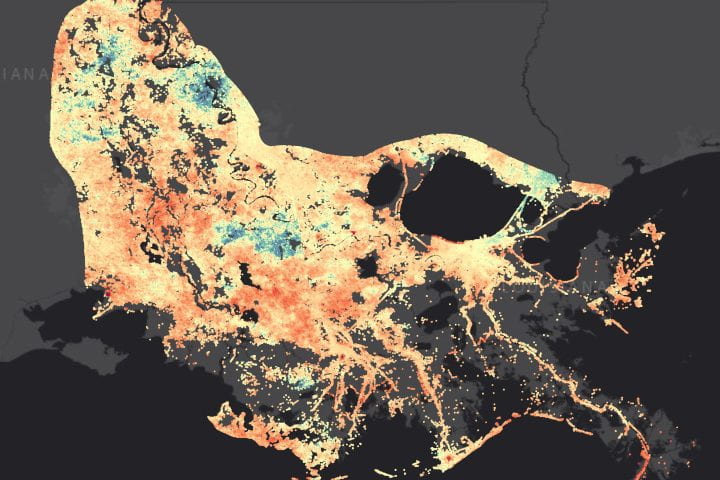



Tinggalkan Balasan